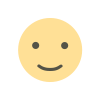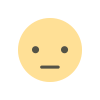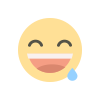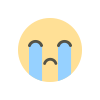Toleransi akan Tumbang di Hadapan Politik Identitas?

Politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Politik identitas bisa menjadi peluru paling ampuh dalam proses pemenangan seorang figur dalam momen pemilu. (Ilustrasi hijaupopuler.id)
Tahapan pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilu 2024 tengah belangsung, mesin-mesin partai tak lagi senyap, mereka bahkan sudah terang-terangan menancap gas untuk bersosialisasi. Kebebasan berdemokrasi tentunya juga menjadi nilai plus bagi orang-orang untuk terlibat ke dalamnya. Demokrasi telah menyediakan ruang untuk berbagai macam ideologi, ide, moralitas, dan bahkan juga identitas. Demokrasi telah menyediakan ruang untuk segala macam perbedaan melalui sebuah kontestasi politik.
Negara ini menginginkan perbedaan-perbedaan yang ada dapat diterima dan disatukan dalam satu tatanan. Namun nyatanya, perbedaan-perbedaan ini kerap kali dijadikan sebuah alasan untuk saling menjatuhkan, menggunakan sebuah identitas untuk saling menyalahkan. Inilah yang biasa disebut dengan politik identitas.
Politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Politik identitas bisa menjadi peluru paling ampuh dalam proses pemenangan seorang figur dalam momen pemilu. Dilihat dari dampak dari politik identitas, hal ini juga cukup serius karena bisa digunakan untuk menyerang golongan tertentu yang akhirnya menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi.
Melihat dari sejarah perpolitikan di Indoensia, salah satu peristiwa yang mencerminkan wajah politik identitas di negara ini adalah saat Pemilihan Gubernur DKI pada 2017 lalu.
Masih teringat jelas, saat itu Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Bahkan pemilihan tersebut dianggap sebagai yang terkotor, mempolarisasi, dan paling memecahbelah bangsa.
Salah satu tanda bahwa sikap moderat dan pluralis di Indonesia dikalahkan oleh kelompok islam radikal kala itu, adalah saat pasangan Anies-Sandi berhasil mengalahkan pasangan petahana Ahok-Djarot. Kemenangan Anies-Sandi, saat itu karena didukung partai Islam sayap kanan seperti PKS, PPP, dan juga dikuatkan oleh ormas FPI.
Selama ini Indonesia dikenal mampu menjaga toleransi dan pluralisme antarkelompok agama, namun setelah terjadinya peristiwa di Pilkada DKI ini, menandakan bahwa toleransi dalam demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran.
Kita lihat saja strategi kampanye Anies-Sandi yang bernada religius dan menjurus ke propaganda. Saat itu, ketegangan selama masa kampanye lebih terasa. Hal itu disebabkan karena begitu banyaknya gerakan politik dan strategi politisasi identitas dan agama yang digunakan. Kita lihat saja Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang dimana mereka menuntut Ahok dipenjara atas tuduhan penghinaan agama. Hal ini dinilai sebagai upaya politisasi agama untuk memenangkan Anies Baswedan, dan pada akhirnya Ahok dinyatakan bersalah, perhatian mengenai masa depan demokrasi Indonesia tambah dipertanyakan.
Apakah demokrasi di Indonesia memang telah melenceng jauh? Apabila benar, demokrasi seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai demokrasi yang ideal? Demokrasi bersifat cair dan dinamis. Demokrasi tidak statis dan tidak bisa diperlakukan sebagai sebuah produk yang kaku. Meski kontestasi, konflik, dan konfrontasi terjadi antar kelompok, bukan berarti demokrasi di Indonesia sudah melenceng jauh. Sejak awal sudah dikatakan bahwa demokrasi ini menyediakan ruang untuk berbagai macam ideologi, ide, moralitas, dan juga identitas. Sehingga ruang perbedaan ini harus dicari jalan tengahnya dan dibangun melalui kontestasi politik.
Sementara di sisi lain, Indonesia sejak lama merupakan rumah bagi pluralisme, di mana perbedaan dan keberagaman ada sejak dulu. Politik identitas memang sulit terhindarkan, apalagi sudah masuk pada ranah identitas agama. Kita bisa melihatnya dalam kasus Ahok versus kelompok Islam radikal yang terjadi selama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemarin.
Kelompok Islam radikal sebagai mayoritas memposisikan diri mereka sebagai kelompok muslim. Sementara itu, Ahok diposisikan sebagai kelompok non muslim. Melihat relasi antara kedua pihak tersebut, kita bisa mengatakan bahwa keduanya bekerja sebagai lawan. Kedua pihak memang memperebutkan suatu hal yang sama, yakni kemenangan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, mereka tetap berjalan di bawah sebuah koridor yang disebut Mouffe sebagai shared symbolic space. Shared symbolic space adalah ruang mengekspresikan perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan antar warga negara.
Ini merupakan dinamika Politik, terutama pada masa kampanye. Hal tersebut adalah proses yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk memperkuat suara mereka masing-masing. Kedua pasangan calon memang telah melalui masa kampanye secara fair. Aksi Bela Islam 411 juga legal menurut UUD 1945 ayat 28, dan UU no. 9 tahun 1998. Tidak ada hukum yang dilanggar. Sementara itu, pendukung Ahok juga melakukan metode kampanye. Salah satunya dengan menggandeng beberapa musisi legendaris seperti Slank, Tompi, Sandhy Sandoro, Once dan lainnya menggelar konser bertajuk “Konser Gue Dua” untuk menyampaikan dukungan kepada Ahok dan Djarot.
Dari kampanye tersebut, jika dilihat dari penekanan pesan masing-masing calon, kedua kelompok membawa gagasan yang berbeda saat kampanye. Kelompok Anies Baswedan, yang terdiri atas mayoritas kelompok Islam radikal, saat itu menekankan bahwa memilih pemimpin Non-Muslim dilarang dalam Islam. Sangat jelas terlihat bahwa propaganda tersebut ditujukan supaya pemilih Muslim tidak mendukung Ahok yang notabene adalah seorang Non Muslim. Namun sebaliknya, kelompok pendukung Ahok justru merespon dengan menggaungkan pluralisme, menggaungkan prestasi-prestasi Ahok-Djarot sebagai strategi kampanye mereka untuk menarik pemilih.
Kedua kelompok bekerja sebagai lawan dengan tetap fokus pada pesan yang masing-masing ingin sampaikan kepada para pemilih. Namun setelah melihat hasil akhirnya, kemenangan Anies Baswedan dilihat sebagai pertanda bahwa demokrasi dan pluralisme di Indonesia mengalami kemunduran.
Dari pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah saat ini kita bukan untuk mencari cara bagaimana menyeragamkan masyarakat atau menyatukan berbagai macam ide, moral, dan identitas. Mengeksklusi kelompok tertentu dalam rangka memperbaiki konsensus kolektif yang dipaksakan tidak akan memperbaiki apapun. Inilah saatnya memupuk keberagaman dan perbedaan, sehingga relasi agonis yang terjalin antar kelompok mampu terpelihara dengan baik, dan tidak berubah menjadi relasi yang antagonis.
Soal politik identitas, seharusnya ke depannya tidak terulang lagi. Namun dalam hal ini isu agama, sebenarnya boleh saja kita memunculkan agama sebagai identitas dengan maksud mempertegas warna dan kereligiusan tapi tidak semestinya digunakan untuk menjatuhkan orang atau kelompok lain, apalagi sampai pendiskriminasian hingga menimbulkan perpecahan di bangsa ini. Toleransi tidak tumbang, tapi justru akan tumbuh jika kita rakyat Indonesia yang menghendakinya.
Apa Reaksi Anda?