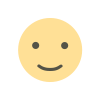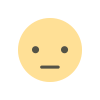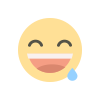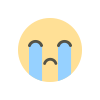Islam di Layar Kaca: Refleksi Representasi dan Dakwah dalam TV

Solusinya bukan menolak media, tetapi mengembalikan orientasi dakwah di televisi pada niat awalnya: menyebarkan nilai Islam dengan keikhlasan dan kecerdasan. Ilustrasi : TV. Lugas/Tirto.
Perspektif | hijaupopuler.id
Setiap bulan Ramadan, layar kaca seolah berubah menjadi ruang suci. Deretan sinetron religi, dan tayangan dakwah memenuhi jam tayang utama televisi. Di sela-sela iklan sabun dan minuman manis, muncul wajah-wajah ustaz dan artis dengan pakaian serba putih.
Suasana seperti ini menghadirkan kesan bahwa televisi telah menjadi mimbar baru bagi umat Islam modern. Namun di balik sorot lampu studio, tersimpan tanya yang lebih dalam: apakah dakwah di televisi benar-benar menyampaikan nilai Islam, atau sekadar mengemasnya menjadi tontonan yang laku di pasaran?
Sejak awal kehadirannya di Indonesia pada tahun 1960-an, televisi telah memainkan peran sosial yang besar. Pada masa itu, TVRI sering menayangkan ceramah dan kuliah subuh yang sederhana tapi penuh makna. Program seperti hikmah fajar menjadi sarana edukasi moral bagi keluarga di seluruh pelosok negeri. Televisi kala itu menjadi medium yang menyatukan umat dalam satu frekuensi, menghadirkan suasana religius tanpa pretensi hiburan berlebihan.
Namun seiring liberasi industri media pada tahun 1990-an, televisi bertransformasi dari media negara menjadi ladang bisnis. Program dakwah pun masuk ke arena kompetisi rating. Muncullah ustaz-ustaz populer yang tampil di berbagai stasiun televisi, membawa gaya ceramah yang ringan, lucu, dan menghibur. Dakwah menjadi bagian dari strategi industri hiburan dan di sinilah dilema itu bermula.
Fenomena “ustaz selebritas” memperlihatkan bagaimana pesan agama bisa kehilangan kedalaman ketika di sajikan untuk menarik penonton. Dakwah di televisi sering kali disesuaikan dengan selera pasar, bukan kebutuhan spiritual masyarakat. Yang paling laris adalah yang paling lucu, paling viral, atau paling dramatis. Pesan moral yang seharusnya menuntun kadang berubah menjadi komedi ringan atau nasihat instan tanpa konteks.
Tidak hanya dalam program ceramah, representasi Islam juga muncul dalam bentuk sinetron religi. Judul-judul seperti hidayah, para pencari tuhan, hingga Islam KTP pernah mewarnai layar kaca. Sinetron-sinetron itu menghadirkan kisah tentang dosa, tobat, dan mukjizat dengan cara yang mudah dicerna. Namun, banyak yang di antaranya jatuh pada pola hitam-putih: yang jahat pasti disiksa, yang baik selalu menang. Padahal, kehidupan dan spiritualitas tidak sesederhana itu.
Televisi memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ia hidup di bawah tekanan rating, iklan, dan kebutuhan audiens. Namun ketika nilai agama diubah menjadi komoditas, muncul risiko besar: Islam direduksi menjadi citra visual yang indah tapi kosong. Dakwah kehilangan kedalaman reflektifnya dan berubah menjadi konsumsi massal yang cepat terlupakan begitu acara usai.
Ada pula persoalan representasi: tayangan religi sering kali menampilkan Islam yang seragam, identik dengan pakaian tertentu, bahasa tertentu, bahkan gaya hidup tertentu. Padahal, Islam itu luas dan beragam. Gambaran yang terlalu sempit di televisi bisa menimbulkan kesan eksklusif, seolah-olah hanya kelompok tertentu yang benar-benar “islami”. Media secara tidak sadar, membentuk persepsi kolektif tentang siapa yang dianggap saleh dan siapa yang tidak.
Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa televisi memiliki kekuatan besar dalam menyebarkan nilai kebaikan. Banyak orang menemukan inspirasi, bahkan berubah menjadi lebih religius setelah menonton tayangan tertentu. Kisah-kisah tobat dan kemanusiaan yang disiarkan di layar kaca sering kali menyentuh hati. Inilah paradoks televisi: ia bisa menjadi sarana dakwah yang mulia, tapi juga jebakan bagi komersialisasi agama.
Refleksi ini membawa kita pada pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya tujuan dakwah di televisi? Apakah untuk menyampaikan nilai-nilai Islam secara mendalam, atau sekadar mengisi ruang tayang dengan label “religi”? ketika niat dakwah mulai berbaur dengan kepentingan industri, batas antara ibadah dan bisnis menjadi kabur. Dan di titik inilah keikhlasan mulai diuji.
Bagi sebagian masyarakat, dakwah di televisi masih dianggap cukup efektif karena dapat menjangkau banyak orang sekaligus. Namun efektivitas itu belum tentu sebanding dengan kedalaman pemahaman yang dihasilkan. Banyak penonton menikmati tayangan religi tanpa benar-benar mengalami perubahan moral atau spiritual. Dakwah yang terlalu cepat dan dangkal berisiko menjadi sekadar hiburan spiritual yang menenangkan sesaat, bukan yang menumbuhkan kesadaran.
Media televisi, pada hakikatnya, bekerja dengan bahasa visual, dan visual sering kali menipu kesan. Cahaya, kostum, dan musik bisa membuat pesan terlihat religius meski isinya ringan. Di sinilah perlunya kesadaran kritis penonton: tidak semua yang tampak “Islami” di layar benar-benar menyampaikan pesan Islam yang utuh. Kita perlu menonton dengan hati, bukan hanya dengan mata.
Refleksi ini seharusnya tidak berhenti pada kritik. Umat Islam sebagai penonton dan pelaku media juga perlu membangun budaya menonton yang lebih selektif. Kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak tayangan religi, tapi juga tayangan yang mendidik, reflektif, dan menyentuh persoalan kemanusiaan. Dakwah di layar kaca harus mengajak berpikir, bukan sekadar membuat tersenyum.
Solusinya bukan menolak media, tetapi mengembalikan orientasi dakwah di televisi pada niat awalnya: menyebarkan nilai Islam dengan keikhlasan dan kecerdasan. Diperlukan kolaborasi antara ulama, jurnalis, dan sineas untuk menciptakan tayangan yang berakar pada nilai Islam sekaligus adaptif terhadap budaya populer.
Penonton pun perlu berperan aktif sebagai penyaring makna, bukan sekadar konsumen. Televisi, dengan segala kekurangannya, masih bisa menjadi sarana dakwah yang agung asalkan kita tidak melupakan ruhnya. Sebab, cahaya dakwah sejati tidak bersumber dari lampu studio, melainkan dari hati yang tulus dalam menyampaikan kebenaran.
Nurfadillah | Mahasiswi KPI FUAD UIN Palopo
Apa Reaksi Anda?