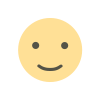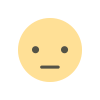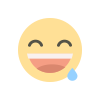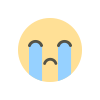Memahami Mahar dalam Perspektif Cinta, Syariat dan Akhlak
Biarkan mahar menjadi saksi cinta, bukan beban sosial. Biarkan pernikahan dimulai dengan berkah, bukan tuntutan. Ilustrasi/foto : detik.com dan penulis.
Perspektif | hijaupopuler.id
Di tengah gempuran budaya modern yang serba cepat, konsep mahar sering kali disalahpahami. Ada yang menganggap mahar sekadar formalitas saat akad nikah, ada pula yang memaknainya sebagai “harga” perempuan—seakan-akan perempuan bisa “dibeli” dengan sejumlah uang dan barang.
Padahal dalam Islam, mahar bukan transaksi jual-beli dan bukan pula tolok ukur mahal-murahnya perempuan. Mahar adalah simbol penghormatan, cinta, dan komitmen seorang laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya.
Dalam Alquran, Allah swt memerintahkan para suami untuk memberikan mahar dengan penuh ketulusan. Surah An-Nisa ayat 4 menegaskan,
“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Jika mereka dengan rela melepaskan sebagian dari mahar itu kepada kalian, maka makanlah (ambillah) dengan senang hati.”
Ayat ini menegaskan dua makna penting, bahwa mahar merupakan hak penuh perempuan, dan pemberiannya harus dilandasi kerelaan—bukan keterpaksaan apalagi pamer sosial.
Mahar: Antara Syariat dan Akhlak
Secara fikih, para ulama sepakat bahwa mahar hukumnya wajib diberikan kepada perempuan saat akad pernikahan. Imam Syafi’i dalam Al-Umm menegaskan hal ini, dan rujukan fikih lainnya seperti Mughni al-Muhtaj karya Al-Khatib asy-Syirbini, menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian untuk perempuan karena akad nikah, hubungan suami-istri, atau hilangnya keperawanan.
Namun lebih dalam dari hukum, terdapat dimensi akhlak dalam mahar. Mahar adalah ungkapan cinta yang jujur (shidq). Ia bukan alat gengsi keluarga, bukan ajang kompetisi, dan bukan pula beban sosial bagi calon suami. Di sinilah nilai etika Islam tampil sangat indah; mahar yang sedikit tetapi berkah lebih utama daripada mahar berlimpah tapi penuh tuntutan dan pamer.
Rasulullah saw bersabda,
“Pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan biayanya.” (HR. Ahmad)
Hadis ini seolah menjadi kritik sosial bagi fenomena hari ini—dimana mahar dan biaya pesta kadang tidak lagi menjadi ibadah, tetapi beban ekonomi dan ajang pencitraan keluarga.
Jenis-jenis Mahar dan Kebijaksanaan di Baliknya
Mahar tidak selalu harus berupa uang atau emas. Yang terpenting adalah mahar bernilai, halal, bermanfaat, dan tidak merendahkan perempuan.
Dalam fikih terdapat dua jenis mahar,
Pertama, mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disepakati besarannya saat akad nikah. Jika pasangan sudah menjalani hubungan suami-istri, maka mahar ini wajib diberikan secara penuh.
Kedua, mahar mitsil, yaitu mahar yang besarnya disesuaikan dengan standar mahar perempuan setara dalam keluarga atau lingkungannya—misalnya mahar kakak perempuan, bibi, atau sepupu.
Keduanya menunjukkan bahwa Islam fleksibel. Tujuan mahar bukan membebani, tetapi memberi penghargaan.
Menariknya, mahar boleh diberikan tunai, dicicil, atau ditunda, sesuai kesepakatan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa mahar termasuk imbal balik akad, sehingga boleh diberikan bertahap seperti halnya pembayaran dalam transaksi muamalah yang sah.
Mengapa Mahar Menjadi Hak Penuh Perempuan?
Yang sering dilupakan adalah fakta bahwa mahar bukan diberikan kepada orang tua atau wali, tetapi menjadi hak milik pribadi perempuan. Suami tidak boleh memanfaatkan mahar tersebut tanpa izin istrinya. Jika mahar belum diberikan saat suami meninggal, mahar itu menjadi utang yang harus dilunasi sebelum warisan dibagi.
Lalu mengapa Islam memberikan hak ini kepada perempuan? Karena Islam melihat bahwa perempuan memikul tanggung jawab besar setelah menikah; mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Mahar menjadi bentuk penghormatan sekaligus perlindungan finansial bagi perempuan.
Sayangnya, hari ini justru muncul fenomena sebaliknya, di mana perempuan dianggap mahal karena mahar yang tinggi—padahal yang sesungguhnya mahal adalah kehormatan, martabat, dan amanah besar yang ia emban dalam rumah tangga.
Mahar Rasulullah saw: Sederhana Namun Penuh Makna
Contoh terbaik tentu datang dari Rasulullah saw. Mahar beliau sebagaimana disebut dalam riwayat Muslim, adalah 12.5 uqiyah atau setara 500 dirham, yang jika dikonversikan ke emas hari ini mencapai lebih dari 1.9 kg emas untuk sembilan istrinya. Namun, beberapa istrinya menerima mahar yang nilai materialnya tidak besar, tetapi bermakna, seperti hafalan Alquran.
Pesan dari keteladanan Rasulullah saw ini jelas, yakni bahwa nilai mahar bukan sekadar angka, tetapi keberkahan dan kerelaan.
Ketika Tradisi dan Budaya Mengalihkan Makna
Pada beberapa budaya, mahar berubah menjadi ajang perlombaan, bahkan “tarif” untuk menikahi seorang perempuan. Inilah yang membuat banyak laki-laki takut menikah, karena merasa belum mampu memenuhi standar sosial yang tinggi.
Padahal, perempuan itu mahal bukan karena angka maharnya, tetapi karena harga diri dan kemuliaan yang Islam letakkan di pundaknya.
Mahar yang terlalu tinggi dapat mempersulit pernikahan, menunda kebaikan, bahkan membuka jalan pada maksiat. Perempuan berhak dihargai, tetapi tidak dengan memberatkan laki-laki hingga merasa hina sebelum berumah tangga.
Penutup: Kembali ke Esensi
Jika kita memahami makna mahar secara jernih, kita akan menemukan keindahan Islam dalam menyeimbangkan syariat, akhlak, dan cinta. Mahar adalah bukti keseriusan dan tanggung jawab laki-laki, penghargaan terhadap perempuan, simbol ketulusan dalam memulai rumah tangga, dan sarana menjaga kehormatan dan kesejahteraan perempuan.
Perempuan memang mahal. Tetapi yang dimahalkan adalah marwah dan amanahnya, bukan angka mahar yang dipamerkan.
Biarkan mahar menjadi saksi cinta, bukan beban sosial. Biarkan pernikahan dimulai dengan berkah, bukan tuntutan. Karena keluarga yang kuat dibangun bukan oleh seberapa mahal mahar, tetapi seberapa besar cinta dan tanggung jawab di dalamnya.
Intan Diana Fitriyati MAg | Penulis asal Purwokerto, Jawa Tengah
Apa Reaksi Anda?