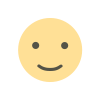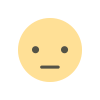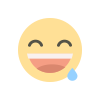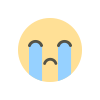Sebuah Otokritik Kepemimpinan di Bumi Lamaranginang

Dalam kajian ekonomi-politik Marx, kelas feodal adalah mereka yang tumbang di tangan revolusi rakyat karena mempertahankan kekuasaan dengan arogansi dan ketertutupan terhadap kritik. Foto : penulis.
Opini | hijaupopuler.id
Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kekuasaan itu seperti cermin; ia memantulkan wajah asli seseorang. Barangkali pepatah itu cocok disematkan pada sosok Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Utara yang akrab disapa Opu Andi Rahim—sebuah sapaan yang konon katanya sarat nilai budaya, tapi juga mengandung aroma peninggalan feodalisme yang belum sepenuhnya punah.
Dalam kajian ekonomi-politik Marx, kelas feodal adalah mereka yang tumbang di tangan revolusi rakyat karena mempertahankan kekuasaan dengan arogansi dan ketertutupan terhadap kritik.
Ironisnya, semangat serupa justru masih terasa di pemerintahan yang mestinya telah bertransformasi menuju tata kelola demokratis. Maka ketika kita menyebut pemerintahan Luwu Utara hari ini “kampungan,” bukan soal gaya berpakaian atau logat daerah, melainkan kampungan dalam cara berpikir dan bersikap terhadap kritik.
Sosok yang Dulu Kritis, Kini Anti Kritik
Saya masih ingat betul, dahulu—iya, dahulu, sebelum beliau menjadi bupati—Andi Rahim dikenal sebagai sosok yang vokal, kritis dan bahkan sering melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan sebelumnya. Dalam banyak kesempatan, tutur katanya tajam, visinya luas, dan idealismenya tampak murni. Saya pun, kala itu, termasuk yang menaruh harapan besar padanya.
Namun, kekuasaan memang punya cara aneh mengubah manusia. Setelah resmi menjabat sebagai Bupati Luwu Utara, yang muncul justru pribadi berbeda; arogan, mudah tersinggung, dan alergi terhadap kritik. Perubahan ini bukan semata soal temperamen, melainkan gejala klasik seorang pemimpin yang terjebak dalam kenikmatan kekuasaan—di mana “kritik” dianggap ancaman, bukan koreksi.
Ketika Premanisme Jadi Bahasa Kekuasaan
Satu contoh yang mencolok adalah peristiwa ketika sekelompok warga minoritas di Rampi menuntut hak mereka. Alih-alih berdialog, preman peliharaan justru diturunkan untuk membungkam suara rakyat.
Pemukulan dan intimidasi terjadi. Ini bukan sekadar tindakan represif, tapi simbol bahwa kekuasaan di tangan yang salah bisa berubah menjadi alat kekerasan sosial.
Bantuan Bencana yang Misterius
Lebih tragis lagi, kasus bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk korban longsor di Minanga. Bantuan itu dikabarkan sudah lama turun, tapi entah menguap ke mana—tidak jelas bentuk, jumlah, maupun wujudnya. Seolah-olah bantuan itu hanyalah mitos yang hidup dari mulut ke mulut.
Dan ketika publik mulai bertanya, ancaman pun datang; intimidasi, laporan polisi, hingga ancaman kekerasan. Semua hanya karena satu hal; berani bersuara.
Pemimpin dengan Kepribadian Ganda
Inilah yang penulis sebut sebagai “kepribadian ganda kekuasaan.” Sebelum berkuasa, tampak merakyat dan kritis; setelah berkuasa, berubah menjadi anti kritik dan represif.
Sebuah transformasi klasik para pejabat daerah yang tak mampu menahan godaan status dan simbol kehormatan feodal. Mungkin inilah alasan mengapa istilah opu seakan kembali hidup bukan sebagai penghormatan budaya, melainkan sebagai pengingat bahwa feodalisme ternyata belum mati di Bumi Lamaranginang.
Penutup
Jika pemerintah Luwu Utara hari ini disebut “kampungan,” maka itu bukan karena warganya, bukan karena budayanya—melainkan karena cara berpikir pemimpinnya yang masih terjebak dalam pola kekuasaan lama; menolak kritik, menutup telinga dan memelihara ketakutan terhadap suara rakyat.
Kritik bukan musuh. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Tapi tampaknya, bagi Opu Andi Rahim dan lingkar kekuasaannya, kritik justru dianggap racun. Dan di situlah penyakit kampungan itu bermula.
Reski Halim | Kader LMND Kota Palopo
Apa Reaksi Anda?