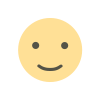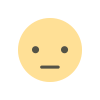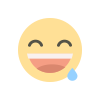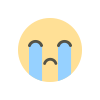Paradoks Pemberdayaan: Ketika Pemberdaya Dipinggirkan dari Panggung Kerakyatan

Dari kaca mata ekonomi kerakyatan, pemberdayaan bukan sekadar program teknokratis, tetapi proyek kebudayaan membangun manusia seutuhnya, dengan akal dan haknya.
Opini | hijaupopuler.id
Dalam narasi besar pembangunan nasional berbasis desa, para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) semestinya berdiri di garda depan sebagai agen pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Mereka bukan sekadar pelengkap administratif dalam urusan Dana Desa, tetapi representasi dari semangat transformasi struktural: mengangkat potensi lokal, menggerakkan partisipasi rakyat, dan membangun kapasitas ekonomi dari bawah.
Namun, ironi mengemuka saat ratusan bahkan ribuan pendamping ini justru diberhentikan karena terlibat dalam kontestasi demokrasi sebagai calon legislatif. Maka lahirlah sebuah paradoks: pemberdaya yang diberhentikan karena berdaya.
Dari kaca mata ekonomi kerakyatan, pemberdayaan bukan sekadar program teknokratis, tetapi proyek kebudayaan membangun manusia seutuhnya, dengan akal dan haknya. Dalam konsep ini, rakyat bukan objek pembangunan, tetapi subjek produksi nilai ekonomi dan sosial.
Ketika para pendamping diberhentikan karena keterlibatan politik, maka yang sesungguhnya dikerdilkan bukan sekadar karier individu, tetapi ruh dari partisipasi rakyat itu sendiri. Bukankah demokrasi dan pemberdayaan berjalan seiring? Lalu mengapa ketika rakyat akar rumput mencoba memasuki ruang kuasa, mereka justru dianggap melampaui batas?
Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika pemecatan ini justru menyembunyikan agenda lain: efisiensi fiskal atau penertiban politik. Bila benar, maka upaya pemberdayaan yang dijalankan selama ini tereduksi menjadi proyek birokrasi, bukan perjuangan rakyat. Ekonomi kerakyatan tidak dapat tumbuh di tanah yang tak subur oleh keadilan dan keberpihakan. Ia menuntut partisipasi yang utuh, dari mulai musyawarah desa hingga mimbar politik.
Peran pendamping desa sangat strategis: mereka menjadi jembatan antara sistem dan warga, antara anggaran negara dan kebutuhan lokal. Bila para pendamping itu memiliki integritas, kapasitas, dan legitimasi sosial, maka keterlibatan mereka dalam politik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai perluasan fungsi pemberdayaan dalam medan demokrasi. Mereka bukan sedang meninggalkan tugas, tetapi sedang naik kelas sebagai pejuang kebijakan berbasis rakyat.
Kita harus waspada: jika pemberdayaan hanya dijalankan selama rakyat patuh dan diam, maka itu bukan pemberdayaan, melainkan pembinaan yang semu. Pemberdayaan sejati mengandung unsur pembebasan: membebaskan dari ketergantungan, dari kemiskinan, dan dari eksklusi politik.
Maka, jika ekonomi kerakyatan hendak ditegakkan secara otentik, maka keputusan pemecatan pendamping desa yang tak berbasis evaluasi objektif justru kontraproduktif. Ia mencederai semangat keadilan distributif, melemahkan partisipasi warga dalam ruang demokrasi, dan pada akhirnya, mempersempit jalan bagi tumbuhnya kemandirian desa.
Pemberdayaan bukan hanya soal mengajari rakyat agar bisa berdiri. Tapi juga tentang memberi mereka hak untuk berjalan ke mana pun mereka inginkan, termasuk ke arah kekuasaan yang selama ini hanya bisa mereka bantu dari luar pagar.
Dr Adzan Noor Bakri SESy MESy | Korpus Abdimas LP2M IAIN Palopo
Apa Reaksi Anda?