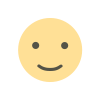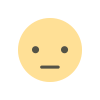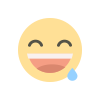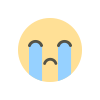Sosok Walid dalam Film Bidaah: Kritik Terhadap Industrialisasi dan Seksualitas Berkedok Agama

Agama ketika disalahgunakan, bisa menjadi senjata berbahaya—dan film harus berani menyuarakan dan mengkritiknya.
Tren | hijaupopuler.id
Film 'Bidaah' dari Malaysia bukan sekadar kisah fiksi tentang kesesatan seorang tokoh bernama Walid—seorang dukun bersurban yang memanipulasi agama untuk memuaskan nafsu dan kekuasaannya.
Lebih dari itu, film ini adalah cermin tajam yang memantulkan fenomena global: penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, bisnis dan kekuasaan.
Di tengah maraknya industri film religi yang kerap mengusung narasi-narasi idealis tentang kesalehan, Bidaah justru berani menampilkan sisi gelap dari mereka yang bersembunyi di balik jubah agama.
Ini bukan hanya kritik terhadap individu seperti Walid, tetapi juga terhadap sistem yang memungkinkan orang-orang seperti itu berkembang: lembaga keagamaan yang dikomersialisasi, sekolah agama yang lebih mementingkan profit daripada pendidikan moral, hingga tokoh-tokoh publik yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi untuk kejahatan.
Agama sebagai komoditas: bisnis film dan industri religi
Di Indonesia dan Malaysia, film-film bertema agama kerap menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Mulai dari sinetron religi, film inspiratif tentang tokoh ulama, hingga konten-konten dakwah yang diproduksi massal—semuanya memiliki pasar yang besar.
Namun di balik nilai spiritual yang dijual, ada pertanyaan kritis: Sejauh mana industri ini benar-benar mendidik, dan sejauh mana ia hanya menjadi alat profit dengan memanfaatkan sentimen keagamaan?
Banyak film agama terjebak dalam romantisasi kesalehan tanpa mengajak penonton berpikir kritis. Tokoh-tokoh ustadz atau kyai sering digambarkan sempurna, tanpa cela, sehingga menciptakan kultus individu.
Padahal dalam realitas, tidak sedikit tokoh agama yang terjerat skandal korupsi, kekerasan seksual, atau bahkan penipuan.
Bidaah hadir sebagai antitesis dari narasi-narasi suci tersebut—mengingatkan kita bahwa di balik simbol-simbol agama, bisa saja terselip niat busuk.
Kritik terhadap penyalahgunaan agama: Walid dan para 'pemangsa spiritual'
Walid adalah metafora sempurna dari para pemangsa spiritual yang menggunakan agama sebagai alat kontrol. Ia bukan hanya menipu, tetapi juga membangun sistem ketakutan dengan dalil agama. Korban-korbannya tidak berani melawan karena mereka diyakinkan bahwa perlawanan terhadapnya sama dengan perlawanan kepada Tuhan.
Fenomena ini nyata terjadi di banyak tempat. Di Indonesia, kasus-kasus pelecehan seksual oleh tokoh agama, penipuan atas nama sedekah, hingga pendirian aliran sesat yang mengeruk keuntungan materi, semuanya menunjukkan betapa agama bisa menjadi alat eksploitasi.
Yang lebih berbahaya, ketika masyarakat terlalu takut atau terlalu fanatik untuk mempertanyakan otoritas keagamaan, maka kekerasan dan penyelewengan akan terus berlangsung.
Bisnis film agama: antara edukasi dan eksploitasi
Industri film agama seharusnya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral. Sayangnya, banyak produser dan sutradara lebih memilih formula aman: mengulang-ulang cerita tentang mukjizat, pertobatan dramatis, atau konflik hitam-putih antara yang 'saleh' dan 'dosa.' Jarang ada yang berani seperti Bidaah—mengangkat sisi gelap dari mereka yang mengaku suci.
Jika film-film agama hanya menjadi alat propaganda kesalehan semu, maka ia ikut berkontribusi pada budaya toxic yang memuja simbol tanpa substansi. Masyarakat diajarkan untuk mengagumi figur tertentu tanpa kritis, dan itu berbahaya.
Kekerasan seksual dan kekuasaan: ketika agama jadi tameng
Salah satu poin terkuat Bidaah adalah penggambaran kekerasan seksual yang dilegitimasi oleh otoritas agama. Ini bukan fenomena fiksi. Di negara kita, kasus serupa telah terungkap—mulai dari pesantren, gereja, hingga organisasi keagamaan. Pelaku sering kali lolos karena korban takut dianggap menodai agama jika bersuara.
Film seperti Bidaah ini penting karena ia memecah kebisuan. Ia memaksa penonton untuk bertanya: berapa banyak Walid-walid lainnya di sekitar kita?
Kesimpulan: perlunya film agama yang kritis
Bidaah bukan sekadar film, ia adalah kritik sosial. Ia mengajak kita untuk mempertanyakan:
Pertama, bagaimana agama bisa menjadi komoditas bisnis, baik di film maupun dunia nyata?
Kedua, mengapa masyarakat mudah terpesona oleh simbol-simbol agama tanpa memeriksa integritas pemakainya?
Ketiga, sejauh mana industri film agama berkontribusi pada kultus individu atau justru melawan penyalahgunaan kuasa?
Jika bisnis film agama ingin benar-benar bermakna, ia harus berani keluar dari zona nyaman. Tidak hanya menampilkan kisah inspiratif, tetapi juga membongkar hipokrisi dalam sistem keagamaan itu sendiri.
Sebab agama ketika disalahgunakan, bisa menjadi senjata paling berbahaya—dan film harus berani menjadi suara yang mengkritiknya.
Dr Muhammad Ash-Shiddiqy ME | Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah
Apa Reaksi Anda?