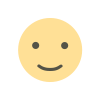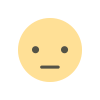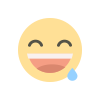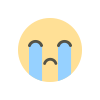Konflik Daerah, Mengingat Kembali Warisan Leluhur yang Terlupakan
Pada masa kerajaan di Sulsel, khususnya bagi masyarakat Bugis Makassar, berlaku hukum adat yang sangat mempertimbangkan nilai siri’ atau harga diri alias kehormatan.
Opini | hijaupopuler.id
Belum cukup sebulan lalu, kembali terjadi konflik 'daerah' di Sulawesi Selatan (Sulsel) tepatnya di Kota Makassar. Wilayah yang dikenal mempunyai nilai utama yang diwariskan oleh para leluhur, yang mengajarkan etika dasar dalam kontak sosial masyarakatnya.
Nilai utama tersebut dikenal dengan sebutan tiga S, sipakalebbi (saling memuliakan), sipakatau (memanusiakan manusia) dan sipakainge (saling mengingatkan).
Sulsel mempunyai sejarah panjang dalam dinamika sosial dan pemerintahan kerajaan. Dalam catatan sejarah, abad ke-9 menjadi awal peradaban di tana ini, ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Luwu pada abad ke-9, Kerajaan Gowa dan Bone pada abad ke-14.
Dari segi kekuatan, ketuaan kerajaan, hingga luas wilayah menjadikan tiga kerajaan tersebut mempunyai pengaruh dan termasuk kerajaan cukup besar pada masanya.
Sulsel yang mempunyai luas wilayah sekira 46.717 km², disatukan oleh tiga etnis utama, yaitu Bugis, Makassar dan Toraja, namun ketiga etnis tersebut mempunyai masing-masing sub etnis, seperti Mandar, Duri dan lain sebagainya.
Suku Bugis mendiami wilayah antara lain Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Pare-pare, Pinrang, Sidrap. Mereka juga tersebar di daerah lain seperti Luwu dan Enrekang. Suku Makassar mendiami wilayah Gowa, Makassar, Maros, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Selayar. Walaupun beberapa daerah terjadi percampuran Suku, seperti Pangkep, Sinjai dan lain-lain.
Konflik yang terjadi di Makassar beberapa waktu lalu oleh oknum sekelompok pemuda, antara Luwu dan Makassar, yang diduga dipicu penikaman yang dilakukan oknum Wija To Luwu (WTL) di wilayah Makassar, mengingatkan kita pada konflik internal antara kerajaan di Sulsel, termasuk antara kerajaan Bugis dan Makassar.
Konflik seperti ini di masa pemerintahan kerajaan tidak jarang ditemui, namun tidak sampai memicu terjadinya peperangan antar kerajaan, lumrahnya terjadi penikaman disebabkan belum adanya hukum tertulis yang mengikat setiap perlakuan keseharian masyarakat Sulsel.
Pada masa kerajaan di Sulsel, khususnya bagi masyarakat Bugis dan Makassar, hukum yang berlaku adalah hukum adat yang sangat mempertimbangkan nilai siri’ (harga diri dan kehormatan).
Biasanya jika terjadi kasus seperti penikaman atau pembunuhan di wilayah sendiri oleh suku lain, hukum yang diberlakukan adalah hukum adat. Hukum adat bertujuan memulihkan nilai siri’.
Pertanyaannya kemudian, kenapa nilai siri’ harus dipulihkan dalam proses pemberlakuan hukum adat?
Secara umum siri’ berarti harga diri, martabat dan kehormatan, dan banyak orang dalam mempertahankannya dan berujung pada pertumpahan darah dan pembunuhan.
Definisi tersebut tidak salah karena ilmuan barat dan peneliti asal barat mendefinisikan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka lihat, sedangkan masyarakat Sulsel yang seharusnya berbicara banyak tentang warisan leluhurnya.
Dalam masyarakat Sulsel khususnya Bugis Makassar, memaknai kata siri’ sebagai sistem sosio kultural dan kepribadian yang menjadi pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.
Siri’ tidak selalu disandingkan dengan sesuatu yang negatif, namun ia adalah perwujudan akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keimanan dan kesungguhan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.
Nilai siri’ dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna, sehingga bila terjadi kasus yang berujung pertumpahan darah maka harga diri atau siri’ menjadi pembenaran mereka melakukan tindak kekerasan.
Hukum Adat dalam Menyelesaikan Perkara
Dalam masyarakat Sulsel, yang berperkara seperti kasus penikaman yang terjadi pada suatu wilayah oleh suku lain biasanya dilakukan pemulihan siri’ terlebih dahulu, karena hukum adat berpusat pada konsep siri’ (harga diri/kehormatan).
Pelanggaran terhadap siri’ akan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan memicu reaksi balasan, sehingga pemulihan siri’ kehormatan dianggap perlu sebagai langkah awal.
Salah satu bentuk penyelesaian konflik adalah melibatkan masyarakat adat sebagai mediator pemulihan harga diri, dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban.
Biasanya sanksi berupa pengusiran menjadi alternatif penyelesaian perkara sehingga tidak memakan korban yang lebih banyak, namun solusi terakhir yang lebih adil adalah sigajang laleng lipa’, dimana dua orang yang berselisih akan bertarung menggunakan badik dalam sarung. Ini adalah jalan terakhir demi memulihkan kembali siri’ yang hilang.
Warisan Leluhur yang Dilupakan
Konflik daerah yang marak terjadi hari ini yang menimbulkan sikap pembalasan oleh sekelompok orang, merupakan tindakan yang tidak pernah diajarkan oleh leluhur masyarakat Sulsel.
Konsep siri’ sering dijadikan sebagai pembenaran dalam melakukan tindakan pembalasan, sedangkan para leluhur masyarakat Sulsel mengajarkan nilai utama dalam kontak sosial yang dikenal dengan sebutan sipakalebbi dan sipakatau.
Bahkan dalam proses penyelesaian perkara dalam hukum adat Sulsel, lebih mengutamakan pemulihan harga diri terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan reaksi pembalasan dari pihak korban yang kehilangan kehormatannya atas tindakan tersebut.
Masyarakat Sulsel hari ini, sulit dipungkiri sudah jauh dari kebudayaan leluhur mereka, kebudayaan yang merupakan akar dari suatu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Kebudayaan membentuk identitas, nilai-nilai, norma dan cara hidup suatu kelompok masyarakat, yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpikir, berperilaku hingga berinteraksi satu sama lain, sehingga masyarakat khususnya Sulsel tidak sepatutnya meninggalkan kebudayaan.
Muhammad Akbar | Mahasiswa IAI DDI Mangkoso, Ketua Kaderisasi PC PMII Kabupaten Barru
Apa Reaksi Anda?